Kolusi Merapuhkan Demokrasi
Saturday, 25 March 2017 - 00:00
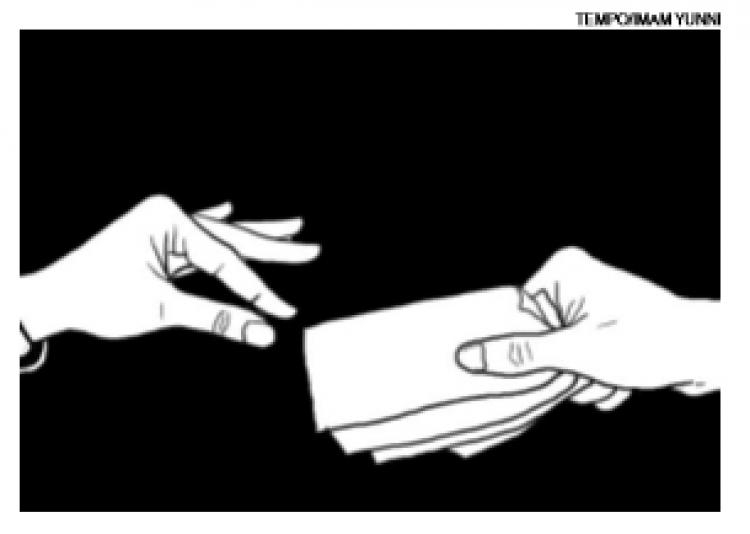
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
Kasus Banten barangkali agak sedikit berbeda dengan Kabupaten Klaten. Dalam konteks Klaten, bupati menjadi tersangka karena menerima suap dari penem patan berbagai jabatan birokrasi, atau yang dikenal sebagai skandal jual-beli jabatan. Skandal ini menjual wewenang kepala daerah melalui mekanisme pasar. Artinya, siapa yang sanggup membayar, dialah yang akan mendapatkan posisi itu.
Jika kemudian terjadi persekongkolan antara mereka yang membeli posisi dan pejabat di atasnya untuk mencuri uang publik (APBD), itu adalah tahap konsolidasi elite politik lokal dan birokrasi yang sama-sama berambisi untuk melipatgandakan aset dan memperluas kekuasaan mereka. Tak mengherankan jika banyak ditemukan profil kekayaan pejabat di daerah yang tidak sesuai dengan penerimaan atau pendapatan resmi mereka.
Apa yang terjadi dalam dua kasus di atas juga menjelaskan bagaimana motif korupsi sudah begitu mengakar pada sebagian besar pejabat publik kita. Pada satu sisi, kita bisa saja menempatkan status para pejabat birokrasi yang terseret kasus korupsi di atas sebagai korban dari kekuasaan dan ambisi politik kepala daerah atau keluarganya.
Pada sisi lain, kita juga dapat memposisikan me reka sebagai salah satu pelakunya lantaran mereka tetap bisa menolak atau tidak mengambil jabatan itu jika harus membayar. Pendek kata, dengan bergabung dalam jejaring korupsi itu, mereka menjadi kaya-raya dan berkuasa.
Akibat dari politisasi birokrasi yang menggejala di berbagai pemerintahan daerah, banyak agenda dan program pembangunan yang tidak berjalan efektif. Upaya mengentaskan masyarakat miskin, mening katkan akses dan mutu pendidikan rakyat, perbaikan layanan publik di sektor kesehatan, ketersediaan air bersih, kualitas moda transportasi publik dan infrastruktur jalan, hadirnya rasa aman dan nyaman, serta ber bagai macam urusan publik lainnya tak kunjung terwujud. Hal ini karena pe nempatan birokrasi ba nyak yang tidak sejalan dengan prinsip merit dan asas tata kelola pemerintahan yang baik lantaran intervensi politik yang kuat dari kepala daerah.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebenarnya menjadi obat untuk memulihkan birokrasi yang korup, tidak profesional, lamban, malas, dan berbagai persepsi negatif lainnya yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam menilai birokrasi. Salah satu yang menjadi ujung tombak pengawasan program reformasi birokrasi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Salah satu wewenang Komisi adalah memberikan penilaian atas mekanisme promosi, mutasi, dan pengangkatan pejabat tinggi di daerah maupun aparat sipil secara umum. Pada intinya, mekanisme penempatan pejabat tinggi di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengikuti asas good governance dan mengedepankan sistem merit dengan menempatkan kualitas dan integritas personal calon sebagai penentu untuk menempati posisi itu.
Kehadiran dan sepak terjang Komisi dalam tingkat tertentu dapat menghambat upaya konsolidasi kekuasaan di level birokrasi dan memba ngun jarak yang lebih lebar antara pejabat politik dan birokrasi. Bagaimanapun, dalam praktek korupsi yang terjadi di berbagai daerah, kepala daerah membutuhkan instrumen birokrasi untuk mengeksekusi atau mewujudkan ambisi mereka.
Tanpa birokrasi, pejabat politik mengalami kesulitan, misalnya untuk mengatur secara teknis proyekproyek APBD yang akan dibagi kepada rekanan dan pengaturan mengenai feenya. Birokrasi juga menjadi penghubung yang efektif antara kepala daerah dan para pengusaha dari ber bagai kelompok kepentingan lainnya.
Jika kemudian ada gagasan dari DPR untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk mengamputasi seluruh wewenang KASN dan membubarkannya, tentu kita menjadi mafhum apa latar belakangnya. Tentu agenda politik DPR untuk merevisi undang-undang itu, salah satunya, merupakan respons atas “keluhan” kepala daerah yang tak lagi leluasa menempatkan orang-orangnya di pos-pos strategis. Mereka tak bisa lagi serta-merta mengangkat individu yang dianggap berjasa dalam pemenangan pilkada atau menunjuk bekas anggota tim sukses mereka untuk menjadi pejabat daerah.
Undang-undang itu telah menutup sebagian akses mereka terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi daerah karena adanya mekanisme lelang jabatan dan berbagai macam prasyarat lain dalam mempromosikan, mengangkat, dan memutasi aparat sipil. Dengan kata lain, undangundang itu dan eksistensi Komisi telah berhasil memutus relasi patronase antara elite politik lokal dan birokrasi. Sayangnya, di luar wacana revisi Undang-Undang KPK yang juga telah bergulir, secara perlahan kita juga akan menyaksikan akrobat politik lain untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Adnan Topan Husodo, koordinator ICW
Tulisan ini disalin dari Koran Tempo, JUMAT, 24 MARET 2017










